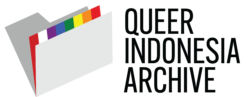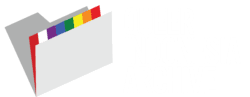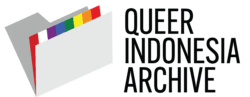Mengenang Bunda Dorce yang Abadi atas Waktu

Dorce dalam balutan kebaya Jawa: Foto - CNN, 2018
Setiap kisah hidup seorang queer di Indonesia, bukan hanya penting dikenang sebagai individu, melainkan punya makna politis bagi representasi queer. Saya menegaskan bahwa ia (yang queer) penting dikenang mengingat kehadiran kita (sebagai queer) yang seringkali dilupakan dan terhapus oleh waktu. Kita dapat hilang atau tak diakui dalam silsilah keluarga atau sistem birokrasi negara. Jika pun tidak dimaksudkan demikian, seringkali kita tetap “hilang” sebab, bagaimana sejarah itu dibentuk, enggan mengakomodir identitas yang queer. Bahwa menjadi queer seolah aib, memalukan, dan tak pantas dikenang. Dan dengan kebencian itu, mereka membangun tembok yang kokoh untuk membuat kita tak lagi dapat dilihat. Sejarah telah menampilkan wajahnya yang angkuh untuk mendesak kita mudah dilupakan. Maka, setiap kabar duka atas satu saja dari kita yang gugur, merupakan pertanda untuk kita bertarung melawan waktu agar kenangan tentangnya jangan sampai ikut terkubur.
Perenungan tersebut menguat ketika saya mendengar berita Dorce Gamalama yang menghembuskan napas terakhirnya pada 16 Februari 2022 lalu. Sosoknya sebagai ikon yang multi-talenta, bukan sekadar harus kita ingat dalam sejarah industri hiburan atau budaya pop di Tanah Air, tetapi juga karena kisah hidup Dorce tak terlepas dari konteks sejarah maupun trajektori gerakan perjuangan hak LGBTIQ+ di Indonesia.
Saya menghabiskan masa kanak-kanak di era 1990-an ketika karier Dorce tengah meroket. Saya tinggal tak jauh dari salah satu kediamannya. Kala kecil, saya bersama anak-anak sebaya lainnya kerap iseng “bertualang” sore melewati tempat tinggalnya atau rumah gadang-nya yang sempat ia jadikan tempat menyimpan segala memorabilia selayaknya museum kecil. Saya pernah melihat di televisi, ada berlemari-lemari baju yang pernah dikenakannya di sana. Saya pun berkawan dengan seseorang yang menjadi tetangganya itu. Kawan saya tinggal persis di sebelah rumah gadang Dorce. Ia kerap berbagi cerita tentang sosok Dorce yang dermawan. Kelompok pengajian ibu-ibu dipinjamkannya ruang untuk berkumpul. Ada ratusan anak yatim yang diampu Dorce sebagai sosok bunda yang sejatinya memang ideal atas konstruksi “ibu” kala itu. Saya mengagumi perjuangannya merebut pengakuan atas klaim retorika “bunda” (keibuan) yang didefinisikan oleh kultur atau nilai yang heteronormatif tersebut.
Dorce mengawali karier melalui Fantastic Dolls, sebuah kelompok seni yang beranggotakan para waria atau transpuan. Fantastic Dolls sendiri telah populer pada 1970-an dan 1980-an di bawah kepemimpinan Ibu Myrna. Pada akhir dekade 1960-an, – ketika bahkan gerakan LGBTIQ+ modern belum lahir – kelompok transgender perempuan (kala itu sempat disebut “wadam” sebelum akhirnya berganti menjadi “waria,” “transgender,” dan “transpuan,” di mana ketiga kata itu masih kontekstual untuk dipakai hingga kini) telah mulai mengorganisir diri dalam beragam organisasi informal dan kelompok seni. Hal itu bergulir menjadi pondasi penting dalam gerakan trans di Indonesia (dalam sejarah yang bisa tercatat) ketika secara resmi dan politis, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) lahir (diprediksi tahun 1969) di Jakarta dan disusul dengan berdirinya Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) pada 13 November 1978 di Surabaya, Jawa Timur. (Ada kemungkinan atas keberadaan organisasi wadam/waria/transpuan lain di Jakarta atau Surabaya atau kota lain, tapi saya hanya menyebutkan dua organisasi itu karena keduanya adalah yang dapat ditelusuri dalam sejarah yang tercatat dan bisa saya temukan sejauh ini.) Sementara itu, gerakan LGBT modern secara resmi ada di Indonesia ketika Lambda Indonesia hadir pada 1 Maret 1982 di Solo, Jawa Tengah. Baik itu HIWAD atau Fantastic Dolls maupun kelompok atau organisasi waria/transpuan yang berafiliasi dengan keduanya di Jakarta, telah melahirkan para aktivis waria/transpuan generasi awal, termasuk Ibu Myrna, Ibu Nancy Iskandar, dan Ibu Lenny Sugiharto (kini Ketua Yayasan Srikandi Sejati). Seiring dengan itu, berbagai organisasi dan kelompok seni/hiburan yang beranggotakan waria pun tumbuh di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia sepanjang tahun 1970-an maupun 1980-an.

Penampilan Fantastic Dolls pada sebuah acara di Ancol, Jakarta tahun 1986 - Foto: Majalah Tempo
Di puncak popularitasnya, Fantastic Dolls memiliki Dorce dan Ibu Myrna yang memberikan Dorce nama yang hingga akhir hayatnya dipakai Dorce sebagai nama depan atau nama panggungnya. Dorce kelak menambahkan “Gamalama” (nama tengah) pada awal 1980-an yang diambil dari nama gunung di Ternate, Maluku Utara ketika ia berkunjung ke sana bersama Benyamin Sueb – aktor yang pernah menjadi pemain utama dalam Betty Bencong Slebor (1978) dan “Halimatusadiah” (nama Belakang) usai ia menunaikan ibadah haji pada 1990.
Era 1980-an menjadi tahun-tahun yang menantang bagi Dorce sebab ia melakukan transisi di hampir semua aspek. Dan yang paling mengagumkan dan penting bagi kita untuk menaruh hormat padanya, adalah fakta bahwa ia telah menggapai “piala” kemenangan atas seluruh perjuangan itu melalui eksistensinya di dunia hiburan.
Ketika masih bergabung di Fantastic Dolls, Chenny Han – juga alumni dari kelompok tersebut – mengibaratkan Dorce dan Bu Myrna bagai sepiring sajian komplit lauk dan kerupuk untuk kekompakan mereka dalam menghibur. Dorce pun terlibat dalam film yang berkisah tentang waria/transpuan dan dimotori oleh kelompok waria/transpuan sendiri, yaitu Mereka Memang Ada (1982). Popularitas film itu ditunjukkan dengan keberadaan album kaset yang menjadi soundtrack film tersebut, di mana Dorce ikut menyumbangkan dua lagu. Satu tahun setelah rilisnya film itu, Dorce mengambil langkah besar untuk melakukan transisi medis usai mengalami perenungan spiritual dengan berbincang bersama Tuhan yang memantapkan niatnya melakukan transisi sebagai perempuan. Meski sempat dijatuhkan oleh dokter, ia tak patah semangat dan terus mencari hingga akhirnya ia dipertemukan dengan dokter spesialis bedah plastik Djohansjah Marzoeki.

Album kaset untuk film Mereka Memang Ada
Prof. Dr. dr. Djohansjah Marzoeki, Sp. BP. yang menangani Dorce, mengungkapkan (pada Angin Malam episode 42 “Perjalanan Dorce Menuju Operasi Plastik”) bahwa selain dirinya, ada tim yang terdiri dari dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dokter genetika, psikiater, psikolog, dan lainnya yang ikut memeriksa untuk meyakinkan “calon ini (Dorce) bukan dibuat-buat atau mencontoh, tapi didorong dari dirinya (dengan) tekadnya (yang) sudah bulat.” Itu tentu bukan yang pertama terjadi di Indonesia, tapi sorotan publik yang besar kala itu, mengubah pandangan banyak orang, termasuk para dokter/ahli yang berhasil diyakinkan oleh Dorce.

Sebuah artikel pada majalah Tempo (1989) tentang transisi medis waria/transpuan di Indonesia.
Usai menjalani operasi, ia kerap membalas cibiran atau memuaskan rasa penasaran orang dengan lelucon. Dorce seringkali memuji dirinya sendiri yang cantik atau manis dan berkata “tak menyesal walau ‘burung’-ku dipotong.” Pada perempuan (straight), ia mungkin mengutarakan kalau “kau (perempuan) kelak bisa beranak, (tapi) aku cuma bisa kasih enak.” Itu hanya beberapa kutipan yang bisa saya ingat.
Tak berhenti pada transisi sosial dan medis, bermodal rujukan dari para dokter/ahli, Dorce pergi ke pengadilan untuk melakukan transisi legal. “Aku ingin diakui negara,” katanya pada acara bincang-bincang televisi yang sama bersama Djohansjah. Dan seiring dengan itu, ia melakukan pendekatan dengan sejumlah ulama dalam “menantang” tafsir Islam atas transisi dirinya. Vivian Rubiyanti mungkin menjadi transpuan Indonesia pertama yang melakukan transisi medis dan legal, di mana kisahnya turut difilmkan dalam Akulah Vivian (1977). Tapi, bisa jadi adalah Dorce yang pertama menegaskan transisi religius dalam Islam yang disorot publik atau media. Baginya itu penting mengingat masyarakat kita yang didominasi oleh Muslim, hukum agama Islam yang diakui dalam sistem hukum negara (terutama hukum perkawinan), dan identitas Dorce sebagai Muslim. Selain melakukan pendekatan dengan para ulama, Dorce merespons keraguan orang atas kesalehannya sebagai perempuan Muslim dengan berkontribusi pada pembangunan pesantren dan masjid. Pada pertengahan 1980-an, Dorce diputuskan (diakui negara) sebagai perempuan. Tak lama kemudian, ia menikahi seorang lelaki, lantas menyandang gelar “hajah” sebagai perempuan Muslim yang telah menjalankan ibadah haji ke Mekkah. Ia juga mengangkat tiga orang anak dan – kemungkinan hingga kini – telah menyantuni ribuan anak yatim.
Dorce pernah berada pada kondisi sebagai target atas kebencian publik yang menghujamnya dengan cacian dan makian. Tapi, di saat yang sama, mungkin ada lebih dari banyak orang yang pula tak bisa menyangkal atas kegembiraan yang telah ia kontribusikan dalam panggung hiburan sekaligus atas kedermawanannya pada banyak hal.
Ia bilang, “Aku terlahir kembali” usai pulang dari Tanah Suci sebagai perempuan.
Setelah meledaknya film Dorce Sok Akrab (1989) dan Dorce Ketemu Jodoh (1990), kariernya di dalam dunia hiburan melesat tajam sebagai aktris, penyanyi, pencipta lagu, pelawak, seniman, pembawa acara, dan lain-lain. Wajahnya menghiasi layar kaca sepanjang dekade 1990-an. Ia hadir di banyak film, sinetron, dan acara bincang-bincang dengan aktif pula mengeluarkan album musik. Ia mendapat rekor Museum Rekor Indonesia atas peluncuran sembilan album sekaligus dalam lima bulan. Pada 2005-2009, ia pun memiliki acara dengan namanya sendiri dan sempat dinominasikan sebagai program talkshow terbaik: yakni Dorce Show. Dari sana, ia akrab dengan sapaan Bunda Dorce.
Tentu saja, setelah Reformasi ‘98 – tepatnya, pasca-Pilpres 2009 – yang diikuti dengan kebangkitan gerakan fundamentalisme dan populisme agama, gerakan LGBTIQ+ mulai menghadapi situasi yang tak pernah diduga sebelumnya. Sementara itu, kita terlanjur mengenal Bunda Dorce sebagai perempuan saleh.

Dorce dalam balutan jilbab yang secara konsisten ia kenakan sebagai perempuan Muslim.
Usai talkshow-nya diberhentikan, kehidupan pribadi Dorce turut dijadikan objek perbincangan dengan mengaitkannya pada ragam tafsir Islam yang konservatif. Ia sendiri – dengan segala capaian yang telah diperjuangkannya – bahkan ikut menghadapi situasi yang menantang sebagai imbas dari pengkambinghitaman “LGBT” di Indonesia yang dimotori oleh para ulama konservatif, politisi, dan pejabat di era demokrasi liberal. Berangsur-angsur, sosoknya meredup dari berbagai panggung diikuti dengan merosotnya kondisi kesehatannya.
Bahkan, menjelang akhir hidupnya, berbagai kontroversi masih terus bermunculan, di mana para ustadz selebriti tak sungkan menjadikan kehidupan dan sosok Bunda Dorce sebagai objek untuk mereka mendapatkan perhatian dan sorotan publik.
Tapi, Bunda Dorce tak pernah tunduk dan kisah hidupnya telah menegaskan eksistensi dan signifikansi dari makna representasi seorang sosok transpuan sebagai perempuan dengan banyak piala yang telah mengobarkan banyak aspirasi dan inspirasi bagi kaum queer, terutama waria/transpuan di Indonesia.
Kita akan terus terkenang pada petuah bijaknya bahwa “kesempurnaan hanya milik Allah” – bukan para dokter/ahli, ulama/ustadz, politisi, dan negara.
Melalui esai ini, QIA hendak meluaskan panggilan bagi siapa pun yang memiliki dan bersedia menyumbangkan berbagai arsip (foto, artikel pada media cetak, buku, album, dan lainnya) terkait Bunda Dorce sebab kenangan apa pun tentangnya yang terwujud dalam beragam bentuk arsip, merupakan jejak yang menjadi bagian dari mozaik yang memperkaya warna-warni orang-orang queer maupun perjuangan kita. Dan melalui gerakan pengarsipan atas kisah hidup Bunda Dorce (dan para sosok queer senior lainnya), kita menyerukan perlawanan untuk dilupakan atau dimusnahkan dalam sejarah kita sebagai bagian dari Indonesia.
Ini adalah artikel perdana yang menjadi bagian dari seri esai yang ditulis oleh para penulis tamu kami.

Nurdiyansah Dalidjo
Nurdiyansah Dalidjo adalah seorang penulis queer. Buku terakhirnya yang berjudul Rumah di Tanah Rempah, mengeksplorasi berbagai topik interseksionalitas tentang sejarah atau konteks kolonialisme di Indonesia dari kacamata seorang queer. Berbagai esainya yang menggali berbagai tema LGBTIQ+ dapat dibaca di sini.