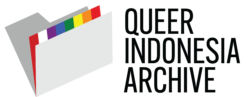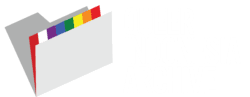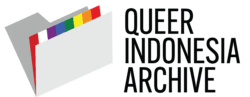Refleksi Beby tentang kisah Yasmin Purba
Ilustrasi: @icankami
Mendengarkan Puan diinisiasi untuk menelusuri dan merekam jejak hidup dan pengalaman perempuan queer di Indonesia.
Kami bertemu Yuli Rustinawati dan Yasmin Purba untuk mendengar bagaimana rasanya tumbuh menjadi seorang perempuan queer yang tinggal di Indonesia. Merekam dan mendengarkan kisah mereka mengantarkan kami pada kisah dan pengalaman perempuan queer yang beragam. Pengalaman ini tidak terpisahkan dari gagasan tentang visibilitas, ketimpangan kelas, misogini, dan homofobia yang berkelindan dan konsisten menjadi momok perempuan queer Indonesia.
Kami mengundang Selira Dian dan Beby, dua perempuan queer muda yang menuliskan esai refleksi mereka berdasarkan apa yang mereka dengar dari rekaman wawancara sejarah lisan ini.
Simak tulisan Beby di bawah
“Aku anak yang keras kepala,” ucap Yasmin Purba yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai seorang lesbian.
Keras kepala menurut Kamus Etimologi Bahasa Indonesia berarti nakal, bandel, tidak mau menurut atau mendengarkan kata orang. Bagi perempuan, ungkapan ini lazim dikenakan terhadap mereka yang tidak mematuhi standar norma sosial tertentu. Sedangkan bagi laki-laki, ungkapan keras kepala terkadang tidak hanya berarti “tidak patuh”, tetapi bisa bermakna “berani”. Keras kepala ini kemudian memiliki makna ganda; tergantung gendernya. Yasmin bertindak sebagai “anak keras kepala” karena penolakannya untuk patuh terhadap norma sosial, yang menopang diri dan identitasnya untuk berjalan dan bertahan sampai detik ini.
Saat ia kecil, Yasmin Purba, atau yang akrab disapa Minke di rumah, mempelajari dua pandangan berbeda tentang ekspresi diri dari kedua orang tuanya.. Dari Mamanya, ia diajarkan untuk mengekspresikan diri secara feminin dengan memakai rok dan dipakaikan lipstick. Ayahnya memberinya kebebasan untuk tampil apa adanya, mendukung ketika Yasmin memilih mengenakan baju yang cenderung “tomboy”. Maka, Minke kecil seringkali melakukan manipulasi atas ketidaknyamanan atas cara didik Mamanya dengan meminta bantuan kepada Papanya. Kondisi ini tak jarang menyebabkan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Cara didik yang tidak konsisten ini menciptakan kebingungan, karena di satu sisi kenyamanan berpakaian tomboy yang direstui Papanya harus disesuaikan saat berhadapan dengan Mamanya karena ia tidak boleh “keras kepala”.
Saat ia kecil, Yasmin Purba, atau yang akrab dipanggil Minke di rumah, mendapatkan dua pandangan berbeda tentang ekspresi diri dari kedua orang tuanya. Ibunya selalu mendorongnya untuk menampilkan sisi femininnya—ibunya sesekali mengungkapkan keinginannya agar Minke kecil mengenakan rok, dan berpesan pada sepupu-sepupunya agar membuat Minke kecil berpenampilan lebih feminin.. Sebaliknya, Ayahnya memberinya kebebasan untuk tampil apa adanya, dan tak pernah ambil pusing ketika Minke kecil memilih mengenakan baju yang cenderung “tomboy”. Dalam mencari keseimbangan antara dua cara berbeda ini, Yasmin kerap kali merasa tidak nyaman dengan pendekatan Ibunya dan mencari dukungan dari Ayahnya..Meski begitu, menurut Yasmin, masa kecilnya terbilang biasa-biasa saja.
“Not the happiest kid in the world, tapi juga tidak [memiliki] masa kecil yang traumatik.” Jika ia merasa orang yang merasa masa kecilnya traumatik berarti tidak suka bernostalgia atas masa itu, ia merasa sering melihat kembali, terutama saat ayahnya masih hidup.. Sikap ayahnya yang selalu mengapresiasi segala bentuk ekspresi diri serta minatnya—mulai dari kesukaan terhadap sejarah hingga berpakaian tomboy—sering ia kenang pasca ayahnya meninggal.
Yasmin juga ingat perasaan pertamanya ketika naksir seorang perempuan waktu Taman Kanak-Kanak. Yasmin waktu TK sering mencari kesempatan untuk melirik dan mendekat kepada perempuan ini. Entah bagaimana, perasaan ini ia anggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak bisa ia ungkapkan pada orang lain secara bebas. “Dulu mungkin gue tahu, tetapi gue ga berani bilang,” dan ketakutan ini juga yang membuatnya kerap membuat cerita bahwa ia menyukai laki-laki sepanjang masa remajanya.
Yasmin selalu membuat cerita bahwa selalu ada laki-laki yang ia suka, dan kegagalan hubungan imajiner dengan laki-laki ini juga selalu dia bubuhi dengan cerita patah hatinya. Setiap dia menyukai perempuan, dia akan menutupinya dengan dalih bahwa dia naksir laki-laki, karena tak dapat mengungkapkan perasaan kepada perempuan yang ia suka.
Orientasi seksualnya memaksa Yasmin untuk membangun dinding pertahanan. Rahasia tentang orientasi seksualnya membuatnya tersudut, bersembunyi di balik topeng keceriaan dan kelucuan. Meski dikenal sebagai seseorang yang selalu ceria dan menjadi pendengar yang baik, dalam hatinya, ia menyimpan dilema mendalam tentang bagaimana mengakui jati dirinya.“Kalau gue out, gue ngomong apa? Gue harus klarifikasi gimana tentang belasan cowo yang pernah gue pura-pura taksir?”.
Yasmin dilela paksa oleh sepupunya saat berusia 35 tahun, hingga mamanya disidang dan diceramahi oleh keluarga besar tentang orientasi seksual anaknya. Mama Yasmin justru bersikap santai dan tidak terlalu banyak ambil pusing atas orientasi seksual anaknya. Sikap mamanya ini ditentang penuh oleh keluarga besarnya dan sering dinasehati tentang orientasi seksual anaknya. Menurut Yasmin, Mamanya selalu punya prinsip “yang penting tidak menyusahkan dia dan orang lain” walaupun tetap menjadi orang Islam taat yang memakai jilbab panjang. Terlebih, pada saat itu Yasmin sudah berganti peran untuk support kebutuhan rumah dan Mamanya. Mungkin akan berbeda ceritanya jika Yasmin dilela sewaktu ia berumur 17 tahun dan bergantung penuh pada Mamanya.
Menjalin hubungan dengan seseorang yang menutupi dirinya, menurut Yasmin, seperti memiliki setengah kaki. Baginya, orientasi seksual merupakan salah satu identitas yang ingin diekspresikan melalui hubungan romantis. Pengalaman ini mengingatkanku pada apa yang juga kualami. Bagiku sendiri, menutup diri terkadang merupakan suatu mekanisme pertahanan; akan tetapi lambat laun merusak kepercayaan diriku dan orang terkasih. Kompleksitas realitas menjalani seorang lesbian terkadang membuat kita mau tidak mau menutup diri, namun di sisi lain ada keinginan dan harapan kuat untuk berteriak ke satu dunia tentang diriku yang sebenarnya. Tentang kekasihku yang sebenarnya.
Kebingungan ini membuat Yasmin merefleksikan ulang diri dan identitasnya. Terlebih, sebelum ia berangkat kuliah di luar negeri ia beranggapan bahwa Amerika Serikat akan lebih “menerima” orientasi seksualnya. Yasmin justru merasakan hal yang sama ia rasakan di Indonesia. Melalui kebingungan ini, Yasmin berhenti menepis identitasnya dan menerima diri seutuhnya sebagai lesbian. Ia juga mulai terbuka dan curhat dengan teman-teman terdekatnya tentang identitas dan permasalahan-permasalahan cinta yang dihadapi.
Di luar konteks penerimaan sosial dan proses meyakinkan diri, pengalaman hubungan Yasmin dengan perempuan mengalami naik turun layaknya hubungan pada umumnya. . Ia pernah berpacaran dengan seorang perempuan yang kerap selingkuh—mungkin, perempuan itu poliamori—dan membuat dirinya sangat posesif. Sampai pada akhirnya, ia menjalani sebuah hubungan stabil yang membuat dirinya merasa nyaman.
Setelah sepenuhnya melela, Yasmin mulai berkenalan dengan komunitas-komunitas lesbian di Jakarta. Ia dikenalkan pada sebuah komunitas lesbian yang sering kopi darat dan menceritakan permasalahan sehari-hari pada tahun 2011. Komunitas ini dibuat sebagai sarana untuk menyediakan support system satu sama lain.
Setelah berada di komunitas itu selama setahun, Yasmin merasa komunitas tersebut belum menjadi ruang yang cukup aman. Internalized heteronormativity di antara anggotanya menjadi salah satu hal yang tidak membuat nyaman, seperti melontarkan lelucon atas tubuh dan seksualitas yang bagi Yasmin tidak pantas dan seksis. Meski sudah melela, Yasmin tetap memiliki perasaan keterasingan dalam komunitas dengan keterbatasan pengetahuannya tentang komunitas pada masa itu.
Perasaan tersebut rasanya wajar, karena Yasmin sesungguhnya lebih banyak memiliki latar belakang bergiat dalam aktivisme sosial non-LGBT di awal karirnya. Ia banyak berkecimpung di lembaga swadaya masyarakat (NGO) dengan fokus isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ia bergabung dengan YLBHI sejak kuliah di Jakarta, hingga bergabung di Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) yang fokus terhadap isu penghilangan paksa di Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia pada 1997-1998. Isu kekerasan di masa lalu yang ia tekuni juga membuat ia sangat familiar dengan sejarah lisan karena merupakan salah satu alternatif untuk meluruskan kebenaran; melestarikan memori kolektif yang dihapus negara.
Sekarang, Yasmin bekerja dengan fokus isu sama dan mendorong akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan. Sejak 2017, Yasmin tidak lagi bekerja di YLBHI dan lebih berfokus pada isu SOGIE yang merupakan bagian dari kelompok rentan dan tidak boleh didiskriminasi. Ia secara intens melakukan advokasi dari segi pendampingan hukum hingga mendorong Undang-Undang Anti Diskriminasi sampai sekarang.
Identitas yang dimiliki Yasmin memiliki banyak wajah; seperti orang lainnya. Ia adalah seorang lesbian, aktivis hak asasi manusia, teman, dan kekasih. Bagiku sendiri, menjadi seorang lesbian tidak mengurangi suatu bentuk apapun dalam diriku. Semua identitas ini masing-masing hadir dengan porsinya dan saya jalani dengan bahagia.
Beby is a dedicated enthusiast in the realms of intersectional studies and environmental law. a proud member of the queer community and avid learner.