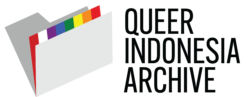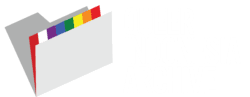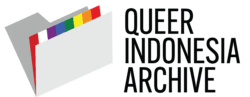Perjalanan Panjang Menyusuri Identitas Diri
Ilustrasi: @icankami
Mendengarkan Puan diinisiasi untuk menelusuri dan merekam jejak hidup dan pengalaman perempuan queer di Indonesia.
Kami bertemu Yuli Rustinawati dan Yasmin Purba untuk mendengar bagaimana rasanya tumbuh menjadi seorang perempuan queer yang tinggal di Indonesia. Merekam dan mendengarkan kisah mereka mengantarkan kami pada kisah dan pengalaman perempuan queer yang beragam. Pengalaman ini tidak terpisahkan dari gagasan tentang visibilitas, ketimpangan kelas, misogini, dan homofobia yang berkelindan dan konsisten menjadi momok perempuan queer Indonesia.
Kami mengundang Selira Dian dan Beby, dua perempuan queer muda yang menuliskan esai refleksi mereka berdasarkan apa yang mereka dengar dari rekaman wawancara sejarah lisan ini.
Simak tulisan Dian di bawah
Berada di baris terdepan dalam memperjuangankan hak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Yuli Rustinawati punya banyak cerita menarik di balik kiprahnya. Dari seorang anak kecil yang hobi main layangan, eksponen reformasi 1998 ini tumbuh menjadi aktivis yang gigih menggalang solidaritas bagi kelompok minoritas.
Jauh sebelum aktif berorganisasi, Iye, sapaan akrabnya, sudah terbiasa hidup dalam suasana kolektif yang riuh khas orang Betawi. Ia tumbuh besar di Jakarta bersama orang tua dan enam saudara kandung: seorang laki-laki, lima perempuan. Dengan formasi ibu dan empat saudara perempuan, Iye terbiasa hidup dengan banyak perempuan.
Hidup dalam nuansa rumah yang feminin, membuat Iye sering diajak kakak perempuannya agar lebih peduli dengan penampilan. Saban akhir pekan, jadilah mereka memotong kuku dan keramas bersama. “Ini gak lucu sih, kakakku bilang, kalau lu mau punya pacar, hal yang harus lu lihat adalah kebersihan kaki kuku dan telinganya,” kata Iye.
Bagi Iye dan sebagian anak perempuan, ajakan ini bisa jadi terasa seperti suruhan untuk mempercantik diri demi memanjakan mata laki-laki. Semacam ada ketakutan semu yang ditanamkan sejak kecil pada perempuan untuk memenuhi standar kecantikan di masyarakat, atau tersisihkan dari lingkup pergaulan, percintaan hingga kesempatan bekerja.
Namun Iye tak terlalu ambil pusing soal ajakan kakaknya. Di luar rumah, Iye malah lebih senang berkawan dengan laki-laki. Bersama mereka, ia asyik bermain layangan, kelereng, kemah-kemahan hingga memanjat genting rumah.
“Bilangin tuh anak lu. Anak perempuan kok begitu,” ujar Iye seraya meniru bapaknya saat menyuruh ibunya menghentikan Iye yang tengah asyik berpanas-panas ria mengejar layangan. Tapi, imbuhnya, alih-alih memarahinya, sang ibu ternyata hanya menyampaikan keluh kesah suaminya tanpa pernah melarang kegiatan Iye secara langsung. “Waktu itu masih sangat normatif, ibuku cuma bilang huss nggak boleh begitu. Aku tipe generasi yang enggak mau jadi curious, jadi menerima informasi apa saja yang ada di TVRI zaman Soeharto,” terangnya.
Karena hobi Iye yang kontras dengan stereotipe anak perempuan, kata boy, kependekan dari tomboy, pun disematkan menjadi nama panggilannya. “Boy woy woy, ntar dulu woy mereka teriak-teriak gitu. Ibuku langsung jawab, ngapain sih gitu. Tapi seingatku nggak ada penolakan darinya,” kata penerima penghargaan Felipa De Souza 2016 ini sembari tertawa.
Kesenangan Iye pada kegiatan yang umumnya dianggap “maskulin” ini makin menjadi seiring ia beranjak dewasa: Di SMA ia ikut taekwondo dan basket, di kampus ia terdaftar sebagai anggota UKM Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA). Iye lanjut bercerita, di momen pelantikannya sebagai anggota MAPALA, tak disangka orang tuanya yang semula kontra malah rela jauh-jauh datang ke kaki Gunung Salak untuk menyaksikan anaknya. Iye merasa, mungkin dukungan bapaknya pada kegiatan itu adalah tindak lanjut dari tawaran bapaknya untuk masuk ABRI sebelum masuk kampus. “Aku pernah ditawarin masuk ABRI, ada saudara ibu yang perempuan masuk dan setelah lulus jadi letnan dua,” ungkapnya.
Iye yang kurang lebih tahu bagaimana watak militeristik dalam pendidikan ABRI langsung menepis tawaran itu. Ia kemudian memilih masuk Diploma Tiga (D3) Akademi Bank Indonesia (ABI) di Matraman, Jakarta Timur.
Pertama Kali Naksir Perempuan
Di luar hobi dan ekspresi, Iye terbuka menceritakan pengalaman romansanya. Drama cinta monyet ala remaja seperti naksir kakak kelas, pacaran dengan anak STM yang gondrong nan metal hingga relasi jangka panjang dengan pacarnya, semua memori itu tak pudar dari ingatannya. “Aku punya pasangan laki-laki sampai tahun 2008 alias sudah bergabung di Arus Pelangi,” ujarnya.

Iye juga selalu ingat momen naksir pertamanya dengan perempuan. Semasa SMP atau SMA, Iye merasa tertarik dengan seorang gadis gedongan di kampung ibunya. “Lah kok anak ini cakep banget ya? Manis banget, dia rambutnya pendek keriting dan naik vespa yang bunyinya klotok klotok klotok,” kenang Iye antusias.
Di awal reformasi arus informasi tentang keberagaman gender dan orientasi seksual non heteronormatif tentu tak sebanyak hari ini. Karenanya tak heran, Iye pada saat itu belum mengeksplor lebih jauh ketertarikan yang ia alami. Kata lesbian baru kemudian ia tahu karena membaca istilah Sentul dan Kantil di koran Poskota. Tipis-tipis ia juga membaca isu seksologi dari artikel yang ditulis Naek L. Tobing, dokter-cum-seksolog kondang kala itu.
Dari media cetak yang serba terbatas, Iye lalu belajar mengeksplorasi wahana internet. Ia mengaku gaptek saat pertama kali berhadapan dengan piranti digital, “Maklum generasi pra internet gue dan mahal juga waktu itu 1 jam 4.000 rupiah,” akunya. Tapi karena kadung penasaran, saban hari selepas menutup usaha bengkelnya, jadilah Iye asyik masyuk berselancar di alam maya. “Aku diajari sama kawanku yang punya warnet itu. Dia sudah pakai Yahoo Messenger duluan. Lalu dia nge-chat aku, mungkin ya dia merasa aku masuk radarnya,” sambungnya.
Kawan itu pula yang mengenalkannya pada ruang percakapan kawan-kawan lesbian. Iye terkejut, ternyata isu yang tabu di dunia nyata begitu cair di dunia maya. “Dari si kawan ini juga aku dikenali sosok yang akhirnya jadi pacar perempuan pertamaku,” kata Iye. Tapi di saat yang bersamaan, ia juga tengah ramai diisukan dengan kakak tingkatnya di MAPALA. “Eh lu lesbian ya? Iya ga ya? Gak juga sih! Aku merasa dia sudah seperti mbakku sendiri, meskipun akhirnya aku tahu dia ternyata lesbian dan suka sama aku,” imbuhnya.
Bersama pacar perempuan pertamanya, Iye menjalin kasih sekitar 2 hingga 3 tahun. di saat yang sama, Iye juga punya pacar laki-laki. Dari kedua relasi itu ia merasa ada keunikan tersendiri, “Kalau sama laki-laki kan ada waktu ngapelnya, misalnya tiap hari apa. Tapi kalau sama perempuan kan gak normatif ya, dia bisa nginep di rumahku. Oh gini ya rasanya? Kok lo ada mulu sih?,” terangnya. Rutinitas menginap ini membuat Iye sempat dituduh lesbian oleh kakaknya.
Intensitas pertemuan yang lebih sering dibanding bersama pacar laki-laki menurut Iye juga berpengaruh pada eksplorasi seksualnya. Misal, sebatas bergandeng tangan dengan pacar laki-laki di muka umum saja ia merasa tabu karena norma sosial dan agama yang mengikat. Perasaan yang berbeda Iye alami saat mengeksplorasi pengalaman seksual bersama perempuan. Iye merasa inferior ketika tubuhnya dikuasai laki-laki. Bersama pacar perempuannya, Ia merasa sama-sama punya kendali dalam relasi yang setara, “Tidak menaruh kekuasaan atas tubuh orang lain. Jadi, aku mulai curious ya, I think like learning each other jadi lebih eksploratif,” ungkapnya.
Mendadak Jadi Aktivis
Bagi mahasiswa era 1996-1998 seperti Iye, rasanya tak peduli apapun jurusan kuliahnya, mayoritas lebih melek isu sosial karena tensi politik yang naik. Dengan nada yang tak kalah naik, Iye menceritakan bagaimana suasana tegang jelang tumbangnya rezim Soeharto.
Sabtu sore 27 Juli 1996, Iye dan kawan-kawan MAPALA baru saja tuntas nongkrong di kampus. Mereka memutuskan pulang ke rumah masing-masing dengan menumpang sebuah bis kota. Namun situasi jalanan tak seperti biasanya, tiba-tiba saja semua kendaraan khususnya di Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat termasuk Matraman lokasi kampus Iye, tak bisa bergerak. Perang suara klakson bersahutan di udara, Iye dan kawan-kawannya mengernyitkan dahi keheranan, sementara penumpang lainnya yang tak tahan bermacet ria di dalam bis akhirnya keluar dan turun ke jalan.
Sengkarut kemacetan ini bukan terjadi tanpa sebab. Iye kemudian menyadari beberapa kendaraan dan gedung telah dibakar. Harapan untuk pulang ke rumah yang berada di ujung Condet segera pupus, Iye dan kawan-kawannya terpaksa balik arah ke kampus. Ada yang ngumpet di belakang kampus, ada yang numpang di kosan kawan. Mereka semua tak bisa pulang ke rumah.
Ternyata hari itu terjadi pengambilan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Massa aksi berada di dua kubu, massa pendukung Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) – peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli).
Di tahun 1997 kondisi Jakarta semakin panas. Krisis moneter membuat ekonomi lumpuh: perusahan bangkrut, angka pengangguran meroket. Utang luar negeri yang terus bertumpuk dan nilai tukar dollar Amerika Serikat yang merosot terhadap rupiah menjadi beberapa alasan krisis terjadi.
Selain akses informasi yang terbatas dan lajunya diawasi pemerintah, mahasiswa sengaja dibungkam secara sistematis: lewat aturan kampus, UKM/pers mahasiswa/BEM, sampai kurikulum yang nirkritis. Semua yang melawan kontan dicap subversif dan rawan hilang. Selain Petrus (penembak misterius) ada pula Tim Mawar,tim kecil yang dibentuk Kopassus Grup IV yang menjadi dalang operasi penculikan aktivis politik pro-demokrasi 1998. “Mereka yang berdiskusi soal pergerakan mahasiswa itu hidup di gorong-gorong (underground). “Sebelum itu kan kejadian Mawar ya, beberapa aktivis juga dia diculik di Cijantung,” sambung Iye.

Sementara elit politik berkontra penuh intrik, rakyat biasa seperti dirinya terombang ambing dalam ketidakpastian hidup. Paceklik ekonomi dan politik akhirnya meledak pada Mei 1998. Iye menjadi salah satu saksi hidup dari porak porandanya Jakarta saat itu. “Dalam kisruh itu juga terjadi pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan penjarahan. Aku lihat di depan kampus kan ada toko Fujifilm, itu semua kamera habis dijarah. Swalayan Yogya di Rawamangun juga habis dibakar,” ungkapnya.
Di tengah kekacauan itu, Iye yang untungnya punya pager, diminta jangan pulang ke rumah oleh orang tuanya, “Jangan pulang, udah rusuh nih di Condet. Setiap toko ditulisin bukan Cina,” sambung Iye seraya menaikan suaranya. Iye kemudian bergabung ke dalam gerakan. Iye bercerita, tiap kampus saat itu punya komite untuk koordinasi mahasiswa, ada Forum Kota (Forkot) dan Forum Bersama (Forbes). Kampus Iye, Trisakti, dan Jayabaya menjadi basis pergerakan mahasiswa di Jakarta Timur. “Aku ikut aksi membawa tuntutan. Tapi aku gak setiap hari di kampus ya, kalau udah seminggu pulang ke rumah buat cuci baju,” katanya.
Beberapa hari sebelum Soeharto lengser, Iye dan kawan-kawannya berhasil masuk ke gedung DPR. Gedung berbentuk kubah setengah lingkaran itu sudah diduduki ribuan mahasiswa. “Aku inget di dalam gedung banyak ruang-ruang punya fraksi-fraksi,” sambungnya. Iye hanya menginap semalam, sementara mahasiswa lainnya secara bergantian “menjaga” gedung DPR selama empat hari.
Pada momen genting itu, Iye merasakan semangat kolektif yang kuat antarmahasiswa. Iye yang beberapa kali meminjamkan pager kepada kawan-kawannya untuk mengabari keluarga di rumah terutama bagi mahasiswa di luar pulau Jawa. “Ada yang pulang buat cuci baju terus balik lagi. Pasokan makanan kami disuplai Suara Ibu Peduli,” ungkapnya.
Dus, kehadiran Sjafrie Sjamsoeddin – wakil Menteri Pertahanan ke gedung DPR saat itu membuat suasana kembali tegang. Iye ingat, tak lama setelahnya aparat militer masuk membawa senapan. Ribuan mahasiswa ditarik ke depan air mancur. Beberapa armada bis sudah disiapkan aparat untuk menyeret mereka dari gedung DPR. “Ya, Kopassus saat itu yang di-elukan ternyata ada skenario lain di balik itu,” imbuh Iye.
Sepulang dari hari berat itu, Iye tak kuasa menahan tangis. “Aku gak mau makan atau merokok. Stres dan menangis sejadi-jadinya. Aku mahasiswa aku gak paham situasi politik ini,” ungkapnya. Empat hari setelah mahasiswa menduduki gedung DPR, keesokan harinya, 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah Orde Baru lengser, suasana justru makin genting. Pergerakan mahasiswa di kampus dan ruang-ruang diskusi dihantui intel yang menyamar jadi gelandangan hingga pedagang asongan. Di tengah situasi represif itu banyak aktivis yang mendirikan LSM.
Mendirikan Arus Pelangi: Belajar SOGIESC dari Nol
Pengalaman jadi “aktivis magang” saat reformasi 1998 membuat kepekaan Iye pada isu HAM meningkat. Ia kemudian bergabung dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Di tengah kesibukannya mengedukasi warga tentang pemilu dan HAM, Iye mendapat tawaran mendirikan Arus Pelangi dari kawan-kawan sesama aktivis di sana – Mak’e Dodo dan King Oey. “Aku ya ayo-ayo aja, karena basisnya kan HAM. Ya baru kemudian tahu ada orang-orang selain hetero. Zamanku masih sangat normatif,” respons Iye.
Di luar lingkaran aktivis PBHI, mereka semakin memperlebar jejaring. Kawan-kawan relawan seperti Leo, Ridho, Freddy, Juli, dan lainnya hingga total 11 orang dari beragam latar belakang bersepakat mendirikan Arus Pelangi pada 2005. Setelahnya, mereka merancang agenda dalam rapat pertama nebeng di kantor Freddy di Menteng, Jakarta Pusat.
Meski sama-sama berpijak HAM, namun Iye mengaku pada awalnya banyak organisasi non LGBT yang menolak mereka mengangkat isu ini. Arus Pelangi pun juga merupakan organisasi advokasi isu LGBT pertama, sehingga Iye dan pendiri lainnya sadar, isu ini tak mudah diangkat, bahkan di kalangan kawan-kawan gay dan transpuan pun merasa gerakan ini masih tabu. Arus Pelangi kemudian mendapat dukungan dari beberapa kawan organisasi HAM lainnya. Mereka justru tertarik dengan isu ini dan terbuka untuk belajar bersama. Iye sebagai salah satu pendiri pun mengaku masih sangat awam dengan SOGIESC, karenanya ia menjadikan Arus Pelangi sebagai wadah belajar dari nol.
Sebagai langkah awal, Arus Pelangi fokus mengadvokasi kasus pembunuhan Vera, seorang transpuan di Purwokerto, Jawa Tengah. Dengan modal serba patungan, mereka berhasil mengurus kasus kriminal itu hingga tuntas. Setelah itu, Arus Pelangi menempati kantor di Tebet, Jakarta Selatan. Di kantor baru, Arus Pelangi kemudian mengorganisir diskusi-diskusi mingguan. Tapi karena situasi dirasa kurang aman bagi kawan-kawan minoritas, terutama karena pernah mengalami penggerebekan, mereka kembali pindah kantor setelah 3-4 tahun menempati kantor pertama, meski masih di sekitar Tebet. “Kami memang terbuka sebagai organisasi LGBT dan di dalam akta notarisnya juga jelas. Pada jaman itu tidak lebih sulit (mengurus akta organisasi LGBT) daripada zaman sekarang,” cerita Iye.
Pindah markas demi ruang aman masih terus Arus Pelangi lakukan hingga memasuki tahun ke-12. Dari gang ke gang, mereka merasakan betul sulitnya hidup sebagai minoritas gender. Arus konservatisme yang meningkat pascareformasi membuat individu maupun organisasi LGBT rawan dipersekusi. Mimpi buruk itu akhirnya dirasakan pula oleh mereka. Ujaran kebencian dan propaganda diskriminatif dari lingkungan sekitar terus mengancam keberadaan mereka, pada 2016—beriringan dengan semakin meningkatnya liputan tentang LGBTQ yang kian membahayakan—akhirnya Arus Pelangi memutuskan hengkang dari Tebet. Soal pengalaman diskriminasi, Arus Pelangi tentu tak sendiri, di waktu yang berdekatan hal ini juga menimpa organisasi transpuan Sanggar Swara.
Pengalaman buruk di markas lama membuat Iye dan kawan-kawan merancang mitigasi dan protokol keamanan untuk kegiatan Arus Pelangi. “Pokoknya udah diatur keamanannya, mana yang perlu dibawa mana yang ditinggal (jika terjadi persekusi). Selama tiga hari kami ngebakarin sampah-sampah print out dan mengamankan server digital,” terangnya.
Selama Covid-19, Iye dan pasangannya menginisiasi rumah aman untuk menampung kawan-kawan LBT yang terdampak. Rumah yang telah disekat-sekat untuk dijadikan kamar-kamar itu sanggup menampung sekira 13 hingga 15 orang. Agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi, mereka berjibaku menggalang donasi. Bahkan Iye tak hanya memkirkan kawan yang ada di rumah aman tersebut, tapi juga keluarga mereka di rumah. “Emak kalian butuh beras? Kalau ada yang butuh aku mintakan. Kami juga menjual pernak-pernik rainbow yang dilelang dapat 7-10 juta, untuk tambahan, kami juga bikin kue dan masker,” ceritanya.
Tertutup Secara Privat, Terbuka Secara Politis
Dalam 11 tahun terakhir, Iye banyak melakukan eksplorasi seksual, pemikiran, dan gaya pacaran bersama partnernya. Setelah banyak belajar tentang seksualitas, Iye dan partnernya menjalani relasi poliamori. Iye menunjukkan buku The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory yang ditulis oleh Dossie Easton and Janet Hardy sebagai buku yang memberinya perspektif lebih dalam tentang poliamori.

Iye pun gemar bercengkrama dengan kawan-kawan lesbian di berbagai acara dari dugem sampai bi-weekly, diskusi khusus lesbian. Iye juga masih ingat beberapa titik kumpul komunitas di Jakarta yang sering ia datangi. Dalam berbagai kesempatan, Iye memperkenalkan Arus Pelangi kepada kawan-kawan lesbian. “Mereka banyak yang belum berorganisasi dan ya kalau punya geng atau punya kelompok itu pasti tapi rumpiannya sebatas relasi belum sampai pemahaman bila ada kekerasan harus bagaimana,” ungkapnya.
Melela sebagai lesbian di komunitas dan kawan-kawan sesama tentunya lain cerita dengan keluarga. Perpaduan tradisi Betawi dan nuansa religi membuat isu non-heteronormatif bukan topik yang mudah untuk diangkat. Paham dengan kondisi ini, Iye punya pendekatan yang unik untuk membuat keluarga terutama ibunya agar sepakat untuk tidak sepakat tentang pilihannya.
Meski tak secara gamblang mengiyakan identitasnya sebagai lesbian pada keluarganya, tapi Iye punya cara sendiri untuk mengatakannya secara non verbal. Saban ada acara Arus Pelangi, ia mengajak serta ibunya. “Lu apa sih? Waria ya? Oh Ines tuh waria ya! dia tanya lagi, lu apaan sih? Ketemu Mas Dodo bilang, lu apaan sih bencong lu? Terus tiba-tiba ada yang tomboy, lu laki apa perempuan sih?” ceritanya sambil tersenyum.
Iye dan kawan-kawan Arus Pelangi sudah maklum dengan sikap ibunya. Menghadirkan ibu di kegiatan-kegiatannya menjadi cara untuk membiasakan sang ibu terpapar dengan perbedaan. “Aku enggak bilang aku siapa, tapi pasti dia tahu dengan bahasanya sendiri,” ungkapnya.
Bagi Iye, setiap orang punya cara uniknya masing-masing untuk bernegosiasi dengan perbedaan prinsip dalam keluarga. “Aku merasa gak penting out dengan mereka. Maksudku secara publik aku out, secara politik aku out,” kata Iye.
Keluarga Iye juga punya caranya sendiri untuk menunjukkan kasih pada Iye. Pernah suatu hari ibunya memberinya uang karena tahu penghasilannya sebagai aktivis tak seberapa, dan ia punya relasi yang erat dengan keponakan-keponakannya. “Ponakan-ponakan aku udah dewasa, aku udah bercucu loh. Mereka sering tanya, tante gimana? Tante Upi mana?” sambungnya.
Di momen pernikahan keponakannya, Iye diberikan selembar baju yang seragam dengan sanak saudaranya pun dengan kakak dan adiknya yang mengajak ibunya menonton Iye saat tampil di media atau acara. Mungkin, seperti Iye yang tak eksplisit memverbalkan identitasnya, keluarganya pun memiliki caranya sendiri untuk bernegosiasi dengan identitas Iye dan menunjukkan kasih sayangnya.
Selira Dian selira dian adalah penulis gim dan jurnalis lepas. Ia nyaman terlibat dalam komunitas keberagaman gender, budaya, dan agama.